
SAZMAN menggosok-gosok matanya beberapa kali. Dia kini terkesima campur terkujat. Manakan tidak, Hartini…gadis yang pernah bertakhta di ruang hatinya dahulu berdiri di hadapannya. Sedangkan…sedangkan yang dia tahu Tini telah gemulah lima tahun sudah. Tini sudah hancur menjadi tanah, barangkali fikirnya. Jadi, siapa wanita cantik ini? Sazman terus terkujat bagai si pikun duda diberi hadiah menaiki kereta Rolls Royce bersama selebriti genit Hollywood. Air liurnya terlekat di tenggorokan dan dia terus terkesima.
“Assalamua’laikum!”
Mata Sazman masih kaku. Kerdipan bagai mengganggu dan terus melongo menyaksikan keindahan ‘Hartini’ yang sudah lima tahun lenyap dari bebola korneanya.
‘Masakan…masakan ini Hartini! Tak mungkin, mungkin orang lain…mungkin kembarnya? Ah! Setahu aku Tini anak gadis tunggal, tiada dua. Yang ada hanya seorang abang dan seorang adik lelaki.’
Menyaksikan kekakuan menguasai suasana. Hartini menyuakan lagi ucapan indah ‘Assalamua’laikum!’
Di kedua pipi gebunya terlekuk dua lelesung pipit. Satu keindahan, ya.. amat indah yang sekian lama lenyap dari himbauan Sazman. Dia menyeluruhi terus kedirian yang masih setia berdiri di hadapannya. Masih, masih Hartini yang dahulu.
Tinggi semampai berbadan agak sederhana, masih tidak terlalu kurus merenceng atau gemuk berisi, masih ‘maintain’ seperti Hartini yang dia puja sebelum ini. Masih mempunyai lekukan kecil menjelma di kedua pipi tatkala senyuman melirik. Masih juga punya mata bundar tetapi redup dan bebola yang hitam sedikit besar lagi cerlang. Tanda orang bijak, pernah dia menyatakan demikian dahulu kepada Hartini.
“Assalamua’laikum!”
Mata Sazman masih kaku. Kerdipan bagai mengganggu dan terus melongo menyaksikan keindahan ‘Hartini’ yang sudah lima tahun lenyap dari bebola korneanya.
‘Masakan…masakan ini Hartini! Tak mungkin, mungkin orang lain…mungkin kembarnya? Ah! Setahu aku Tini anak gadis tunggal, tiada dua. Yang ada hanya seorang abang dan seorang adik lelaki.’
Menyaksikan kekakuan menguasai suasana. Hartini menyuakan lagi ucapan indah ‘Assalamua’laikum!’
Di kedua pipi gebunya terlekuk dua lelesung pipit. Satu keindahan, ya.. amat indah yang sekian lama lenyap dari himbauan Sazman. Dia menyeluruhi terus kedirian yang masih setia berdiri di hadapannya. Masih, masih Hartini yang dahulu.
Tinggi semampai berbadan agak sederhana, masih tidak terlalu kurus merenceng atau gemuk berisi, masih ‘maintain’ seperti Hartini yang dia puja sebelum ini. Masih mempunyai lekukan kecil menjelma di kedua pipi tatkala senyuman melirik. Masih juga punya mata bundar tetapi redup dan bebola yang hitam sedikit besar lagi cerlang. Tanda orang bijak, pernah dia menyatakan demikian dahulu kepada Hartini.
Muka bujur sirih masih membujur juga, tiada tanda-tanda akan bersegi atau membulat. Dan pigmen putih kekuningan kulitnya masih sama. Tahi lalat hitam masih setia memagut dagu kirinya. Dan getar suaranya yang memanjat deria telinga itulah yang menoktahkan segala. Satu panggilan sahaja sudah mampu membuatkan gegendangnya mencerap dengan baik, itulah dia Hartininya. Hartini Yaakob yang telah lama meninggalkannya, lebih lima tahun dahulu!
Sazman menggagahkan diri, menarik nafas sedikit dalam dan menghembusnya dalam kadar sederhana. Dia mengejapkan cengkaman tangannya pada kedua belah pemegang kerusi kayu jati yang tersedia di lobi hospital itu. Dia seolah-olah berusaha mencari serta mengumpulkan segenap kekuatan. Bagaikan semangatnya terbang merewang apabila pertemuan pagi itu terjadi tanpa sedikit pun dirancang.
Sazman menggagahkan diri, menarik nafas sedikit dalam dan menghembusnya dalam kadar sederhana. Dia mengejapkan cengkaman tangannya pada kedua belah pemegang kerusi kayu jati yang tersedia di lobi hospital itu. Dia seolah-olah berusaha mencari serta mengumpulkan segenap kekuatan. Bagaikan semangatnya terbang merewang apabila pertemuan pagi itu terjadi tanpa sedikit pun dirancang.
Adakah dia di alam fantasi? Mustahil, manusia lain masih sibuk bersimpang siur di sekelilingnya. Para jururawat berbaju putih lengkap masih laju ke hulu ke hilir. Para doktor yang sengaja kekadang menyangkutkan stetoskop ke tengkuknya juga masih berkejaran dan berpapasan laju. Sesekali juga dia masih mampu menancap pada bising dan kederuan suara pelbagai ragam manusia yang menguasai suasana, yang agak bingar namun masih terkawal dan diganggu juga dengan talunan suaran lunak dari pembesar suara membuat pengumuman.
Dengan dada yang masih sedikit berombak laju dan gemuruh darah yang masih belum mereda, Sazman menggagahkan dirinya bangun. Dia membetulkan kaca matanya yang sedikit melurut ke bawah lantaran batang hidungnya bukanlah terlalu ‘begak’ bagaikan hero-hero Bollywood yang tampan. Hidung Melayu asli kata Hartini satu masa dahulu.
Sedikit kegoncangan dan masih dalam kondisi mengawal diri serta emosi. Dia menjawab salam, jawapan yang masih berisi getar dan ketar. Lantaran dia sendiri merasa masih gugup dalam debar. Biarlah, jika ini benar Hartininya dahulu, ia adalah satu keajaiban dari Tuhan. Bukankah Allah itu Maha Pencipta, Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan. Hartini adalah makhluk ciptaan-Nya sama seperti dirinya juga. Jika memang benar gadis tinggi semampai bermata bundar berlekuk di pipi berkulit putih kekuningan ini adalah Hartini yang dahulu, ia adalah ciptaan Tuhan juga. Bukankah setiap malam Jumaat dia dan jemaah di surau depan rumahnya akan membaca surah Yaasin dan bukankah di dalam surah itu ada menyatakan perihal kekuasaan Allah: Sesungguhnya, apabila Dia mengekehendaki sesuatu itu terjadi maka Dia hanya menyatakan: Jadi, maka jadilah ia.” (Yaasin: 82).
Begitulah, lantas dengan sedikit semangat yang kian pulih dan persoalan yang memenuhi cepu minda kian tersisih diisi rasa bertuah pula, Sazman akhirnya kembali normal. Dia menyeluruhi lagi gadis di hadapannya. Ternyata, Hartini kini sudah pun menjadi seperti apa yang diidaminya lima tahun dahulu. Dia mengenakan kot putih berserta stetoskop yang tersimpan rapi di kocek jubah putih itu, namun masih menjulur keluar penekapnya. Dia nampak matang sekali, ditambah dengan tudung yang meliputi sekujur wajah anggunnya itu, dan di dadanya yang bidang itu tertera tanda nama: Dr Hartini. Menuntaskan segala persoalan dan kini dia tambah yakin bahawa dia bukan di alam mimpi lagi.
“Sazman bukan? Sazman Ghazali, pelajar Perubatan Sesi 1994/ 95 UKM? Pernah dimarah Prof. Salam kerana memainkan kemaluan spesimen semasa sesi autopsi di dewan anatomi. Betulkan?”
Agh…Sazman terpaku dalam kepanaan sekali lagi. Sungguh terakam dalam memorinya, itulah kejadian pertama yang paling memalukan. Dia dimarahi oleh Prof. Salam dan seterusnya dia didenda menyiapkan tugas lain yang bertimpa-timpa hanya lantaran dia memainkan alat kemaluan sampel mayat yang dibedah oleh mereka sekumpulan. Kala itulah, Hartini adalah sabahagian daripada ahli kumpulannya. Dan dia sedari awal terlalu nakal. Mahu menguasai suasana dan tanpa duga mengundang amarah sang penyelia tua itu. Lanjutan ceritanya pasti ada, tapi biarlah ia disisipkan pada bahagian-bahagian yang lain pula.
“Hartini Yaacob, maaf Hartini Datuk Yaacob? Pemenang anugerah dekan tahun pertama perubatan UKM? Asal KL bukan?” Sazman menjawab hakikatnya menyoal.
Dengan dada yang masih sedikit berombak laju dan gemuruh darah yang masih belum mereda, Sazman menggagahkan dirinya bangun. Dia membetulkan kaca matanya yang sedikit melurut ke bawah lantaran batang hidungnya bukanlah terlalu ‘begak’ bagaikan hero-hero Bollywood yang tampan. Hidung Melayu asli kata Hartini satu masa dahulu.
Sedikit kegoncangan dan masih dalam kondisi mengawal diri serta emosi. Dia menjawab salam, jawapan yang masih berisi getar dan ketar. Lantaran dia sendiri merasa masih gugup dalam debar. Biarlah, jika ini benar Hartininya dahulu, ia adalah satu keajaiban dari Tuhan. Bukankah Allah itu Maha Pencipta, Dialah yang menghidupkan dan Dialah yang mematikan. Hartini adalah makhluk ciptaan-Nya sama seperti dirinya juga. Jika memang benar gadis tinggi semampai bermata bundar berlekuk di pipi berkulit putih kekuningan ini adalah Hartini yang dahulu, ia adalah ciptaan Tuhan juga. Bukankah setiap malam Jumaat dia dan jemaah di surau depan rumahnya akan membaca surah Yaasin dan bukankah di dalam surah itu ada menyatakan perihal kekuasaan Allah: Sesungguhnya, apabila Dia mengekehendaki sesuatu itu terjadi maka Dia hanya menyatakan: Jadi, maka jadilah ia.” (Yaasin: 82).
Begitulah, lantas dengan sedikit semangat yang kian pulih dan persoalan yang memenuhi cepu minda kian tersisih diisi rasa bertuah pula, Sazman akhirnya kembali normal. Dia menyeluruhi lagi gadis di hadapannya. Ternyata, Hartini kini sudah pun menjadi seperti apa yang diidaminya lima tahun dahulu. Dia mengenakan kot putih berserta stetoskop yang tersimpan rapi di kocek jubah putih itu, namun masih menjulur keluar penekapnya. Dia nampak matang sekali, ditambah dengan tudung yang meliputi sekujur wajah anggunnya itu, dan di dadanya yang bidang itu tertera tanda nama: Dr Hartini. Menuntaskan segala persoalan dan kini dia tambah yakin bahawa dia bukan di alam mimpi lagi.
“Sazman bukan? Sazman Ghazali, pelajar Perubatan Sesi 1994/ 95 UKM? Pernah dimarah Prof. Salam kerana memainkan kemaluan spesimen semasa sesi autopsi di dewan anatomi. Betulkan?”
Agh…Sazman terpaku dalam kepanaan sekali lagi. Sungguh terakam dalam memorinya, itulah kejadian pertama yang paling memalukan. Dia dimarahi oleh Prof. Salam dan seterusnya dia didenda menyiapkan tugas lain yang bertimpa-timpa hanya lantaran dia memainkan alat kemaluan sampel mayat yang dibedah oleh mereka sekumpulan. Kala itulah, Hartini adalah sabahagian daripada ahli kumpulannya. Dan dia sedari awal terlalu nakal. Mahu menguasai suasana dan tanpa duga mengundang amarah sang penyelia tua itu. Lanjutan ceritanya pasti ada, tapi biarlah ia disisipkan pada bahagian-bahagian yang lain pula.
“Hartini Yaacob, maaf Hartini Datuk Yaacob? Pemenang anugerah dekan tahun pertama perubatan UKM? Asal KL bukan?” Sazman menjawab hakikatnya menyoal.
Lalu, tanpa diduga dan tanpa sengaja, pertemuan di Hospital Selayang bagaikan membuka lembaran lama. Sebuah kisah cinta dan pengorbanan. Sebuah kisah duka dan kehilangan. Sazman terasa bagai mahu menarik tubuh semampai itu, mahu dirangkulnya kembali kenangan lalu. Namun, kewajaran sedemikian adalah keterlaluan. Dia hanya pasrah mengecapi sekujur tubuh dan wajah Hartini. Adakah sejarah lama bakal bertaut lagi. Masih adakah ruang dan sedikit pengertian. Dan air mata mulai bergenang di jendela mata Hartini dan Sazman. Biarlah air mata itu menyambungkan kisah selanjutnya. Mereka berdua hilang kata-kata.
_
“Engkau tahun Saz…” satu panggilan teramat manja yang pernah dilagukan satu waktu dahulu. Kehilanganmu adalah satu penyiksaan. Aku penasaran. Aku hampir kandas Saz.”
Mereka mengambil tempat sedikit jauh tersorok dari keributan manusia. Kafetaria aras dua itu memang agak sibuk. Namun, Sazman dan Hartini bagaikan terasing. Mereka teronggong dalam dunia kepiluan. Menggamit sejarah silam yang telah bertaburan lalu cuba mencantumkannya kembali menjadi sebuah gambaran yang serba lengkap. Masakan bisa dilupa segalanya, dua insan itu dulu pernah wujud dalam dunia yang begitu indah dan mereka begitu teruja menuju kedewasaan dalam epilog cinta itu.
“Tapi, engkau menghilang begitu tragis Tini. Engkau mungkin tidak tahu, aku terpaksa memohon waktu bercuti. Ibu bapaku terpaksa menenangkan segalanya. Aku bukan lagi normal masa itu. Aku bagai kalah mengadah qada’ dan qadar Allah. Aku hampir rebah Tini.”
Sazman menekapkan pandangannya ke wajah Hartini yang sesungguhnya masih ayu bahkan semakin ayu. Namun suaranya bergetar menahan sebak. Tubuhnya terasa sedikit tegang. Sungguh dia merasakan, pada waktu itu terlalu banyak cerita yang ingin dikongsi. Begitu banyak yang telah terjadi. Dia sendiri tidak tahu untuk memulakannya di mana. Bagaikan mahu diputarkan sahaja arloji masa, biar mereka kembali pada titik mulanya. Dan dia akan merencanakan kembali sejarah itu mengikut mahunya. Masakan dia berjaya. Masakan.
“Apa sebenarnya berlaku Tini? Pesawat yang engkau naiki dari Amerika Syarikat kononnya dilencong pengganas sebelum merempuh bangunan 99 tingkat Pusat Dagangan Dunia di New York. Aku sahkan itu dari makluman keluargamu sendiri Tini. Engkau dan kedua ibu bapa engkau berkecai, jadi debu berterbangan Tini. Masakan aku lupa.”
Suara Sazman sedikit meninggi. Intonasi yang menggambarkan kekejutan, kepedihan dan kehancuran. Dia parah tika itu, tatkala mengunjungi kediaman Datuk Yaacob di Bukit Damansara mendapatkan kepastian. Masih diingat kejap dalam memorinya, Hairi adik bongsu Hartini menyatakan bahawa kedua ibu bapanya dan kakaknya turut terlibat sama. Semasa itu Hairi sendiri sedang bergegas mahu ke Amerika Syarikat untuk mendapatkan kepastian. Sedang Wisma Putra sendiri mengesahkan bahawa ketiga-tiga nama itu memang tercatat dalam senarai berlepas dari Lapangan Terbang John F. Kennedy.
“Engkau tahu, aku mahu menyertai Hairi ke US. Tapi sayang aku kelewatan. Pasport Antarabangsa aku hilang. Malang sungguh hari itu.”
Hartini bagaikan patung bernyawa, sabar mendengar bait-bait cerita yang tertampan ke gegendang telinganya. Terasa betapa suara yang keluar dari mulut lelaki di hadapannya itu adalah suara kepastian, keikhlasan dan kesungguhan. Dia pasti Sazman serius mengucapkannya.
“Saz, I’m really sorry for what has happened. We didn’t planned it. But everything happened according to Allah’s wish. Apa yang mampu kita lakukan.” Hanya itu yang mampu terucap dari bibir monggel Hartini.
_
“Engkau tahun Saz…” satu panggilan teramat manja yang pernah dilagukan satu waktu dahulu. Kehilanganmu adalah satu penyiksaan. Aku penasaran. Aku hampir kandas Saz.”
Mereka mengambil tempat sedikit jauh tersorok dari keributan manusia. Kafetaria aras dua itu memang agak sibuk. Namun, Sazman dan Hartini bagaikan terasing. Mereka teronggong dalam dunia kepiluan. Menggamit sejarah silam yang telah bertaburan lalu cuba mencantumkannya kembali menjadi sebuah gambaran yang serba lengkap. Masakan bisa dilupa segalanya, dua insan itu dulu pernah wujud dalam dunia yang begitu indah dan mereka begitu teruja menuju kedewasaan dalam epilog cinta itu.
“Tapi, engkau menghilang begitu tragis Tini. Engkau mungkin tidak tahu, aku terpaksa memohon waktu bercuti. Ibu bapaku terpaksa menenangkan segalanya. Aku bukan lagi normal masa itu. Aku bagai kalah mengadah qada’ dan qadar Allah. Aku hampir rebah Tini.”
Sazman menekapkan pandangannya ke wajah Hartini yang sesungguhnya masih ayu bahkan semakin ayu. Namun suaranya bergetar menahan sebak. Tubuhnya terasa sedikit tegang. Sungguh dia merasakan, pada waktu itu terlalu banyak cerita yang ingin dikongsi. Begitu banyak yang telah terjadi. Dia sendiri tidak tahu untuk memulakannya di mana. Bagaikan mahu diputarkan sahaja arloji masa, biar mereka kembali pada titik mulanya. Dan dia akan merencanakan kembali sejarah itu mengikut mahunya. Masakan dia berjaya. Masakan.
“Apa sebenarnya berlaku Tini? Pesawat yang engkau naiki dari Amerika Syarikat kononnya dilencong pengganas sebelum merempuh bangunan 99 tingkat Pusat Dagangan Dunia di New York. Aku sahkan itu dari makluman keluargamu sendiri Tini. Engkau dan kedua ibu bapa engkau berkecai, jadi debu berterbangan Tini. Masakan aku lupa.”
Suara Sazman sedikit meninggi. Intonasi yang menggambarkan kekejutan, kepedihan dan kehancuran. Dia parah tika itu, tatkala mengunjungi kediaman Datuk Yaacob di Bukit Damansara mendapatkan kepastian. Masih diingat kejap dalam memorinya, Hairi adik bongsu Hartini menyatakan bahawa kedua ibu bapanya dan kakaknya turut terlibat sama. Semasa itu Hairi sendiri sedang bergegas mahu ke Amerika Syarikat untuk mendapatkan kepastian. Sedang Wisma Putra sendiri mengesahkan bahawa ketiga-tiga nama itu memang tercatat dalam senarai berlepas dari Lapangan Terbang John F. Kennedy.
“Engkau tahu, aku mahu menyertai Hairi ke US. Tapi sayang aku kelewatan. Pasport Antarabangsa aku hilang. Malang sungguh hari itu.”
Hartini bagaikan patung bernyawa, sabar mendengar bait-bait cerita yang tertampan ke gegendang telinganya. Terasa betapa suara yang keluar dari mulut lelaki di hadapannya itu adalah suara kepastian, keikhlasan dan kesungguhan. Dia pasti Sazman serius mengucapkannya.
“Saz, I’m really sorry for what has happened. We didn’t planned it. But everything happened according to Allah’s wish. Apa yang mampu kita lakukan.” Hanya itu yang mampu terucap dari bibir monggel Hartini.
Memberat terasa di dada. Air mata yang seakan mahu tumpah lagi segera diseka. Pertemuan tanpa duga itu adalah satu yang memedihkan. Namun, lebih pedih apabila Hartini mahu menyelongkar segalanya...
***
Ah...inilah antara cerpen-cerpen saya yang tidak tersiapkan. Banyak sebenarnya yang tergendala. Kekadang, bahkan selalu saya begitu cemburu dengan Faisal Tehrani, umur seusia namun karyanya menjunjung dan membumbung..; sedang saya masih menatih di para-para, masih tersangkut di sigai-sigai...
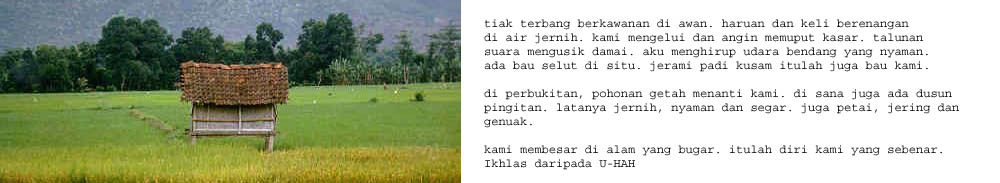



Tiada ulasan:
Catat Ulasan